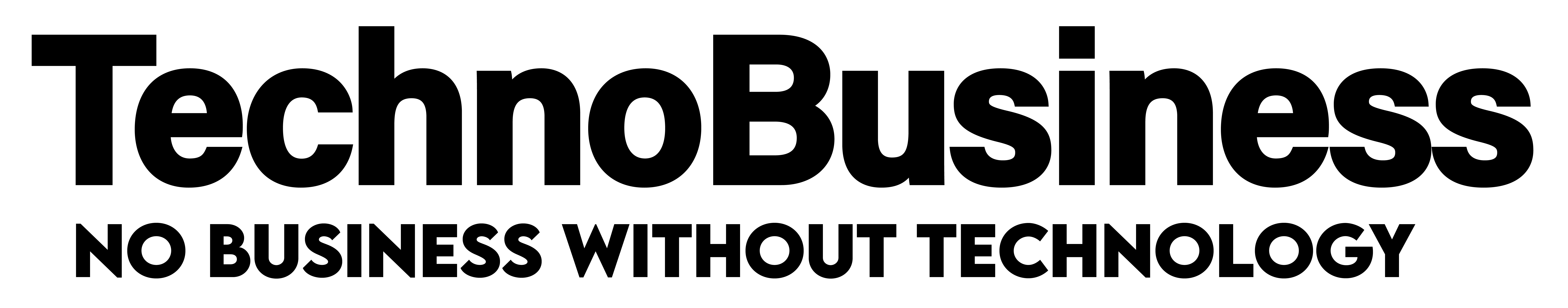TechnoBusiness View
Ketika Makanan Tak Sekadar Pengenyang Perut

TechnoBusiness View ● Anke Dwi Saputro, teman saya yang juga pakar pemasaran, mengirimi saya pesan promosi via WhatsApp Messenger. Pesan singkat itu berbunyi kalau yang namanya Agus bisa makan gratis di Bakso Bom, jaringan waralaba bakso yang dikembangkannya, selama Agustus. Selain teman baik, mungkin dia juga ingat jika nama tengah saya Agus.
Pada Kamis (27/7) malam itu, saat menerima pesan dari Anke, saya masih di kantor. Seraya menyelesaikan pekerjaan, saya menonton televisi. Rupanya hampir semua program berita televisi membahas soal nasi goreng, bukan bakso. Bukan pula makanan yang saya makan malam itu, yaitu sate.
Tentu saja semua stasiun televisi lebih menarik menyoroti nasi goreng ketimbang bakso atau sate. Bukan karena bakso dan sate tidak enak, melainkan nasi gorenglah yang sedang ketiban pulung (kejatuhan keberuntungan). Sebab, malam itu nasi goreng tengah menjadi jamuan pertemuan dua tokoh elite negeri ini, yakni Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan Prabowo Subianto.
Terlepas nasinya dari beras merek Maknyuss—yang sedang dalam penyelidikan atas dugaan pengoplosan—atau tidak, yang jelas nasi goreng itu mendapat pujian dari Prabowo yang Ketua Umum Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra). Lantas, pertemuan di kediaman SBY yang Ketua Umum Partai Demokrat guna merespons besaran Presidential Threshold 20%, yang mereka anggap tak masuk akal, itu kemudian disebut Diplomasi Nasi Goreng.
Beberapa tahun belakangan, terutama sejak dua kekuatan berkoalisi dan beroposisi, harus diakui memang suhu politik di Tanah Air tak pernah dingin. Ada saja isu yang mencuat dan menjadi bahan perbedaan pandangan. Entah besar entah kecil sudah bukan jadi ukuran. Terkadang malah menjurus ke arah isu keamanan. Kalau sudah begitu, diplomasi meja makan menjadi pilihan.
Kita tentu belum lupa dengan langkah Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menemui Prabowo di kediamannya, Hambalang, Bogor, Jawa Barat, pada Oktober lalu. Sebelum diajak menunggang kuda, Jokowi disuguhi nasi goreng oleh mantan rivalnya dalam Pemilihan Presiden 2014 itu. Sejatinya, pertemuan tersebut untuk mendinginkan suasana menjelang unjuk rasa 4 November yang menuntut Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (sekarang sudah mengundurkan diri) dihukum atas dugaan penistaan agama.
Sebulan kemudian, giliran Jokowi yang menjamu Prabowo makan siang di Istana Merdeka, Jakarta. Lalu, pada hari-hari berikutnya, diikuti dengan makan siang bersama para ketua umum partai pendukung pemerintah, salah satunya Megawati Soekarnoputri dari PDI Perjuangan, partai tempat Jokowi bernaung. Sejak saat itu, “makanan-makanan rakyat” seolah naik kelas dan “diplomasi makan bersama” menjadi istilah penghalus dari pertemuan-pertemuan antarelite.
Masalahnya, ketika kaum elite “mengaduk-aduk makanan politik” (yang mungkin ditambahi sambal dari cabai yang mahal dan garam yang mendadak langka), ada sebagian masyarakat yang masih menderita kelaparan. Berdasarkan data Global Hunger Index yang dikeluarkan oleh International Food Policy Research Institute, lembaga riset internasional yang fokus pada pengawasan tingkat kelaparan dan kekurangan gizi di negara berkembang, walau terus menurun, indeks kelaparan di Indonesia pada 2016 masih berada di angka 21,9% (19 juta orang) alias level serius.
Ah, ini kan media bisnis teknologi, untuk apa melantur mengurusi makanan, politik, dan kelaparan. Semula kami tak mau ikut campur dalam perkara itu dan mencoba menyingkirkannya. Tapi, ketika seorang teman menawari bakso, SBY-Prabowo menikmati nasi goreng, dan saya mengenyam sate, persis di waktu yang sama kabar dari Jerman sampai.
Malam itu, melalui e-mail, saya mendapat kabar bahwa pada 7 Juli lalu, bertepatan dengan penyelenggaraan Global Citizen Festival Hamburg, Mastercard dan World Food Programme (WFP) membuat komitmen bersama guna mengatasi kemiskinan dan kelaparan di seluruh dunia. Komitmen itu menggabungkan keahlian Mastercard dalam hal teknologi dan inovasi digital serta upaya WFP menyediakan makanan pokok bagi masyarakat kurang mampu.
Tidak main-main, Mastercard dan WFP menjalankan komitmen mereka dengan cara mengumpulkan dana dan makanan yang dibutuhkan masyarakat melalui kampanye “Seratus Juta Makanan”. Itu merupakan inisiatif global pertama Mastercard bersama WFP. Inisiatif tersebut sekaligus untuk mendukung tekad United Nations Sustainability Development Goals (UNSDG).
Ada empat tekad UNSDG yang dimaksud, antara lain tidak ada kemiskinan (no poverty), tidak ada kelaparan (zero hunger), pendidikan yang berkualitas (quality education), dan kesetaraan gender (gender equality). Karena itu, Mastercard dan WFP siap memenuhi 100 juta persediaan makanan dalam kurun waktu satu tahun ke depan, yang sebelumnya 17 juta makanan.
Yang menarik, di saat pemerintah dan para politisi di banyak negara (termasuk Indonesia) terus sibuk mengaduk-aduk “makanan politik”, sektor swasta berpikir keras memerangi kemiskinan dan kelaparan. Mastercard, misalnya, fokus pada dua area utama: memanfaatkan keahlian dan kampanye berbagi.
Memanfaatkan keahlian, contohnya, pada 2012 Mastercard membantu WFP mempersiapkan sistem perintis untuk membantu menyediakan kartu prabayar bagi para pengungsi Suriah di Libanon dan Yordania. Jadi, lima tahun lalu sebanyak 2,2 juta pengungsi Suriah sudah menggunakan kartu nontunai untuk membeli makanan di toko-toko lokal—saat Indonesia masih memberi bantuan kepada rakyat miskin dengan Bantuan Langsung Tunai.
Di Inggris, Virgin Money, anak perusahaan Virgin Group milik Richard Branson yang didirikan pada 1995, juga pernah menggalang dana dengan hasil setara 250.000 makanan untuk sekolah di Mali. Supermarket dan restoran di Jerman pada 2013 berhasil mengumpulkan dana sebesar €336.000 dari setiap transaksi dan “like” di jejaring sosial Facebook konsumen yang sengaja diperuntukkan bagi pemenuhan makanan sekolah. Di Belgia, pada 2016 Buy Way Personal Finance juga mendonasikan 775.000 makanan untuk sekolah.
Contoh yang baik ditunjukkan Tesco. Jaringan ritel terbesar di Inggris itu, seperti dilansir Metro dan Detikcom, menyumbangkan makanan tak terjualnya ke badan sosial setelah membuang 70 juta makanan pada 2015. Transfernation, perusahaan rintisan berbasis di Manhattan, New York City, Amerika Serikat, sampai-sampai harus membuat aplikasi penyaluran makanan tak terkonsumsi ketimbang dibuang sia-sia kepada kaum duafa yang diberi nama SocialEffort.
Di Indonesia, bukan berarti perusahaan-perusahaan tidak peduli sosial. Namun, kebanyakan di antara mereka fokus memberikan bantuan di bidang pendidikan dan kesehatan yang sesungguhnya juga sudah dijamin pemerintah. Dengan Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Indonesia Sehat yang prabayar, harus diapresiasi pemerintah sudah semakin maju dalam memanfaatkan teknologi penyaluran bantuan kepada rakyatnya.
Soal makanan? Kita berharap tidak sekadar jadi objek diplomasi pemerintah dan para elite politik, tapi juga alat pemangkas indeks kelaparan yang masih amat tinggi secara nyata. Gebrakan-gebrakan perusahaan swasta di luar negeri seperti Mastercard, Virgin Money, dan Transfernation semoga bisa menjadi inspirasi bagi penggalangan bantuan makanan di dalam negeri. Regulasi yang mengharuskan supermarket dan restoran menyalurkan sisa makanannya ke masyarakat menjadi contoh yang lain.
Atau, sekalipun niatnya berpromosi, setidaknya yang dilakukan teman saya, Anke, yang menggratiskan makan bakso bagi yang bernama Agus selama Agustus cukup membantu meringankan sebagian orang, terutama yang bernama Agus seperti saya. Ngomong-ngomong soal bakso, nasi goreng, dan sate, saya kok jadi teringat Presiden Amerika Serikat ke-44 Barack Obama ya. Soalnya, selama dua kali berkunjung ke Indonesia, yaitu pada 2010 dan Juni lalu, Obama selalu menyebut bakso, nasi goreng, dan sate sebagai makanan favoritnya.
Kalau begitu, biarlah saya makan bakso di Bakso Bom secara gratis selama Agustus, SBY dan Prabowo menikmati nasi goreng kala bersama siapa saja. Lalu, satenya? Haha…, sekarang giliran Anda yang makan sate, ya. Sebaiknya sisakan untuk didonasikan kepada tetangga yang membutuhkan tanpa harus ada embel-embel apa-apa.
Ingat, pemilihan umum (pemilu) masih lama, belum membutuhkan juru kampanye. Alih-alih menunggu pemilu, kalau pun waktunya mau dipakai untuk membuat aplikasi semacam SocialEffort, masih cukup kok. Orang Indonesia canggih-canggih, saya yakin Anda bisa. Dengan begitu, perusahaan-perusahaan teknologi bisa turut andil dalam pengentasan kemiskinan dan kelaparan di Tanah Air.●

—Purjono Agus Suhendro
CEO dan Editor in Chief TechnoBusiness Indonesia