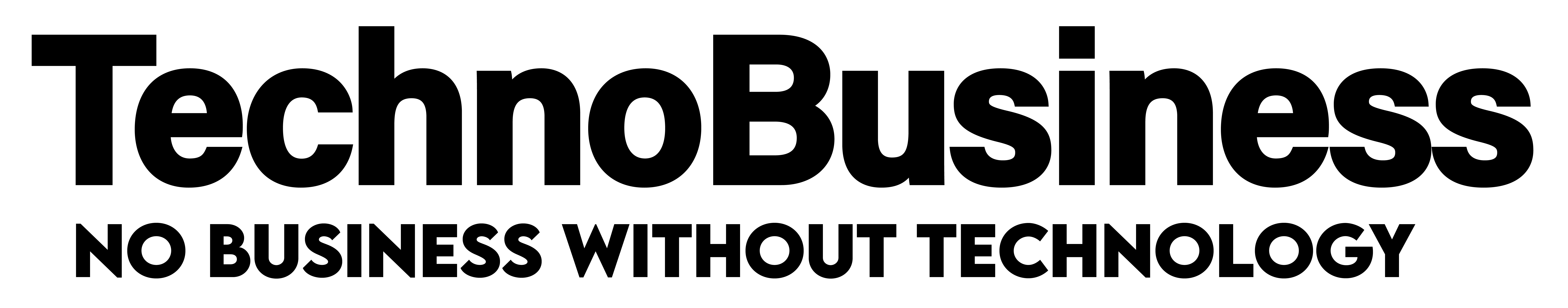TechnoBusiness Opinion
Nokia yang Kepedean

Oleh Jeffrey Bahar, Group Deputy CEO Spire Research and Consulting
Akhir-akhir menjelang pemilihan presiden Amerika Serikat pada 8 November 2016, hampir semua polling memenangkan kandidat dari Partai Demokrat, Hillary Clinton. Donald Trump, sang lawan dari Partai Republik, tidak pernah mendapatkan elektabilitas yang lebih besar. Hillary pun semakin percaya diri (pede) karena perbandingan keterpilihannya kian meninggalkan Trump.

Dalam McClatchy-Marist Poll pada Agustus, misalnya, Hillary memperoleh 48% suara dibandingkan 33% yang memilih Trump. Persentase itu meningkat dari 42% berbanding 39% satu bulan sebelumnya. Elektabilitas yang terus naik itu menjadi bekal bagi Hillary, istri Mantan Presiden Bill Clinton, untuk semakin yakin dirinya bakal memenangi pemilihan presiden yang ke-58 tersebut.
Suara Hillary bertambah dan suara Trump menurun dalam survei lantaran beberapa hal, salah satunya terkait suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Trump dianggap berbahaya karena mengusung SARA dengan hendak membatasi pergerakan kaum muslim jika terpilih menjadi presiden. Rencana konglomerat properti itu memancing reaksi publik dan menganggapnya tak pantas.
Tidak hanya itu, Trump juga akan membuat kebijakan baru bagi imigran, terutama yang datang dari negara-negara Islam dengan melarang masuk ke negaranya. Kebijakan itu ditentang banyak pihak, tidak terkecuali perusahaan-perusahaan teknologi yang berbasis di Silicon Valley, California. Pasalnya, perusahaan-perusahaan teknologi membutuhkan orang-orang berbakat, dan mereka tak sedikit yang datang dari negara-negara yang mendapat ancaman akan dilarang.
 Hingga malam menjelang pemilihan pun, Clinton yang dianggap lebih banyak menyebarkan pesan damai cukup pede akan memenangi pertarungan. Meski dua minggu sebelum pemilihan ia “diganggu” dengan rekomendasi Federal Bureau of Investigation (FBI) atas dugaan skandal e-mail saat menjabat menteri luar negeri, lembaga-lembaga survei dan pengamat-pengamat politik juga tetap mengunggulkan dirinya.
Hingga malam menjelang pemilihan pun, Clinton yang dianggap lebih banyak menyebarkan pesan damai cukup pede akan memenangi pertarungan. Meski dua minggu sebelum pemilihan ia “diganggu” dengan rekomendasi Federal Bureau of Investigation (FBI) atas dugaan skandal e-mail saat menjabat menteri luar negeri, lembaga-lembaga survei dan pengamat-pengamat politik juga tetap mengunggulkan dirinya.
Sepanjang pagi hingga siang pada 8 November 2016 pemilihan presiden Amerika Serikat berlangsung. Semua warga dari 50 negara bagian, Distrik Columbia, dan wilayah administratif lainnya—yang diwakili oleh elektor-elektor presiden menaruh harap kandidat pilihannya memenangi pemilihan. Tidak hanya media lokal, media-media global terus memancarkan laporannya tanpa jeda.
Namun, apa yang terjadi? Pasca-penghitungan suara cepat (quick count) sore harinya, sebagian warga, pengamat politik, dan lembaga-lembaga survei terdiam. Mereka heran, bagaimana mungkin polling yang selalu mengunggulkan Hillary justru secara nyata dimenangi Trump, sang pemicu kontroversi itu? Bagaimana mungkin orang yang banyak menawarkan program tak populer malah disukai warga Amerika?
Sepertinya selama kampanye berlangsung, Hillary memang terlalu percaya diri alias kepedean. Ia menganggap hasil survei sepenuhnya menggambarkan kenyataan, program-program yang mengikuti arus diyakini disukai elektor. Nyatanya tidak. Trump, yang omongannya sering kali menuai kecaman, justru lebih disukai elektor dari electoral-electoral college.
Berdasarkan hasil akhir, Trump memperoleh 270 electoral vote, lebih banyak jika dibandingkan dengan 228 yang didapatkan Hillary. Jumlah electoral vote itu sudah lebih dari cukup karena kandidat presiden Amerika Serikat membutuhkan 270 dukungan elektor untuk berkantor di Gedung Putih.
Berdasarkan hasil akhir, Trump memperoleh 270 electoral vote, lebih banyak jika dibandingkan dengan 228 yang didapatkan Hillary. Jumlah electoral vote itu sudah lebih dari cukup karena kandidat presiden Amerika Serikat membutuhkan 270 dukungan elektor untuk berkantor di Gedung Putih. Setelah itu, para pengamat politik pun berujar bahwa Trump berpegang teguh pada insting dan apa yang ia lakukan itulah yang memang sedang disukai publik Negeri Paman Sam.
Artinya, keunggulan demi keunggulan tidak menjamin seseorang bisa benar-benar memenangkan persaingan, salah satunya dalam pemilihan presiden Amerika Serikat akhir 2016. Buktinya, Hillary yang sudah terlanjur kepedean akibat prediksi-prediksi tersebut malah takluk dari Trump yang tak pernah unggul dalam jajak pendapat sebelumnya.
Tidak di Amerika, tidak di Indonesia. Kita masih ingat betapa Basuki Tjahaja Purnama amat pede akan memenangi pemilihan gubernur DKI Jakarta pada 15 Februari 2017. Basuki, atau yang akrab dipanggil Ahok, sudah jauh-jauh hari yakin akan mengalahkan lawan-lawannya hanya dalam satu putaran pemilihan. Hal itu wajar karena sebagai gubernur, ia menganggap telah bekerja benar, ada hasilnya, dan memberikan banyak sekali perubahan.
 Keberanian Ahok dalam menerapkan kebijakan dan melawan siapa saja yang tidak patuh pada aturan menarik simpati warga. Ia bahkan ingin maju kembali dalam pemilihan gubernur lewat jalur independen karena tak percaya partai politik. Langkah itu pun semakin mengundang dukungan yang terbukti warga bersedia mengumpulkan hingga 1 juta fotokopi kartu tanda penduduk secara sukarela untuk Ahok.
Keberanian Ahok dalam menerapkan kebijakan dan melawan siapa saja yang tidak patuh pada aturan menarik simpati warga. Ia bahkan ingin maju kembali dalam pemilihan gubernur lewat jalur independen karena tak percaya partai politik. Langkah itu pun semakin mengundang dukungan yang terbukti warga bersedia mengumpulkan hingga 1 juta fotokopi kartu tanda penduduk secara sukarela untuk Ahok.
Sayangnya, dukungan yang diyakini besar membuat Ahok kepedean. Saking pede-nya, ia terlalu berani berbicara apa saja, yang kadang-kadang dengan nada kelewat keras. Satu kali, ia pun dituduh menistakan agama. Padahal, publik tidak siap dengan karakter Ahok yang demikian. Elektabilitas Ahok yang di atas 50% lantas turun dan tidak beda jauh dengan Anies Baswedan-Sandiaga Uno dalam pemilihan. Ahok pun tak bisa menang satu putaran.
Ranah Teknologi
 Tidak di dunia politik, tidak di industri teknologi. Yang namanya kepedean, hasilnya pasti tidak bagus. Sebab, terlalu pede bersifat tidak realistis, cenderung berlebihan dengan apa yang seharusnya, tidak sesuai dengan kemauan pasar. Nokia contohnya. Pada awal 2000-an, siapa yang tidak kenal dengan Nokia? Merek asal Finlandia itu menguasai hampir seluruh pasar ponsel global sejak akhir 1990-an hingga 2012.
Tidak di dunia politik, tidak di industri teknologi. Yang namanya kepedean, hasilnya pasti tidak bagus. Sebab, terlalu pede bersifat tidak realistis, cenderung berlebihan dengan apa yang seharusnya, tidak sesuai dengan kemauan pasar. Nokia contohnya. Pada awal 2000-an, siapa yang tidak kenal dengan Nokia? Merek asal Finlandia itu menguasai hampir seluruh pasar ponsel global sejak akhir 1990-an hingga 2012.
Nokia, yang awalnya berupa telepon mobil berukuran besar produksi bersama antara Mobira dan produsen televisi Salora, dengan nama Nokia Mobira Talkman pada 1985, telah berubah menjadi raja ponsel dengan penjualan ratusan juta unit. Nokia 1100, ponsel berfitur layar warna, kamera, dan pesan MMS yang diluncurkan pada 2003, misalnya, terjual hingga 250 juta unit. Seri ini bahkan kembali laris pada 2005.
Namun, kerajaan Nokia mulai goyah setelah raksasa internet Google yang berbasis di Silicon Valley, California, Amerika Serikat, memperkenalkan sistem operasi Android untuk perangkat bergerak. Sistem operasi yang bersifat terbuka (open source) itu lantas dipakai banyak merek, salah satunya Samsung asal Korea Selatan. Penggunaan Android semakin dibutuhkan seiring dengan kebutuhan pengguna untuk mengakses internet melalui ponsel pintar (smartphone).
Nokia yang keukeuh tak mau mengadopsi Android akhirnya mulai tergerus, dan Samsung benar-benar mengalahkan penjualan pendahulunya itu pada awal 2012. Mengacu pada Strategy Analytics, Inc., firma riset dan konsultasi pasar teknologi yang memiliki kantor di Amerika Utara, Eropa, dan Asia, kepedean Nokia untuk tetap menggunakan sistem operasi Symbian berbuah pahit.
Dalam laporan tersebut, pada kuartal pertama 2012 Samsung berhasil menjual 93,5 juta unit ponsel secara global, sedangkan Nokia hanya 82,7 juta unit. Jika dibandingkan dengan penjualan satu model Nokia 1100 pada 2003, tentu tidak sampai separuhnya. Apple, produsen iPhone yang juga mempunyai sistem operasi sendiri, nasibnya sama dengan Nokia, yakni tersalip oleh Samsung karena hanya menjual 35,1 juta unit.
 Rupanya kekalahan itu merupakan awal dari kekalahan-kekalahan berikutnya. Nokia yang tetap merasa pede dengan teknologinya ternyata tak mampu meyakinkan pasar ponsel global. Sejak saat itu penjualan Nokia semakin anjlok, sementara di waktu yang sama Samsung kian mendominasi. Tidak berhenti sampai di situ, sampai-sampai merek ponsel pintar Nokia mesti dilepas ke Microsoft senilai US$7,2 miliar pada 25 April 2014.
Rupanya kekalahan itu merupakan awal dari kekalahan-kekalahan berikutnya. Nokia yang tetap merasa pede dengan teknologinya ternyata tak mampu meyakinkan pasar ponsel global. Sejak saat itu penjualan Nokia semakin anjlok, sementara di waktu yang sama Samsung kian mendominasi. Tidak berhenti sampai di situ, sampai-sampai merek ponsel pintar Nokia mesti dilepas ke Microsoft senilai US$7,2 miliar pada 25 April 2014.
Sampai saat ini, merujuk pada data yang diliris IDC, Nokia belum kembali ke daftar lima besar merek ponsel global. Begitulah, merek yang kepedean, tidak cepat mengadopsi perubahan di zaman yang serba-cepat berubah akibat perkembangan teknologi, akhirnya tersingkir dalam persaingan. Di ranah internet, barangkali Yahoo! bisa menjadi contoh lain, yang kalah dari Google, follower-nya. Di dunia politik pun sama. Buktinya seperti cerita Hillary dan Ahok tadi. Karena itu, di mana pun kita, apa pun bisnis kita, sebaiknya jangan lengah, dan jangan kepedean!**
Data TechnoBusiness
 Spire Research and Consulting merupakan perusahaan periset pasar dan konsultasi bisnis untuk pasar global, terutama di negara-negara berkembang. Perusahaan yang didirikan pada 2000 ini memiliki kantor perwakilan di semua negara Asia Tenggara, ditambah China, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang, dengan kantor pusat di Singapura.
Spire Research and Consulting merupakan perusahaan periset pasar dan konsultasi bisnis untuk pasar global, terutama di negara-negara berkembang. Perusahaan yang didirikan pada 2000 ini memiliki kantor perwakilan di semua negara Asia Tenggara, ditambah China, Amerika Serikat, Korea Selatan, dan Jepang, dengan kantor pusat di Singapura.